Komedi dalam Simbolisme Hukum: Dewi Themis dan Absurditas Pembutaan Mata” – Sidik Permana
- Sidik Permana
- Oct 5, 2025
- 6 min read
Peribahasa “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” sudah tidak relevan. Kenyataannya, penegakan hukum kerap memampang komedi pilu nan absurd tentang lucunya mencari keadilan di Indonesia. Satu sisi vonis 3 bulan kurungan untuk Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao, di sisi lain ada vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan kepada Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono akibat kasus suap Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, sebesar Rp 3,6 miliar. Alih-alih ketidakadilan, kondisi ini lebih tepat disebut absurd.
Indonesia Corruption Watch (ICW) (2016) dalam Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Tahun 2015, menyebut bahwa dari hasil pemantauannya terhadap 524 perkara korupsi dengan 564 terdakwa yang telah diputus pengadilan dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali (PK) di tahun 2015, sebanyak 524 perkara korupsi, yang merugikan negara hingga Rp. 1,7 triliun, memiliki rata-rata vonis hanya 26 bulan atau 2,2 tahun penjara. Detailnya, kategori vonis berat (>10 tahun) hanya 3 orang, sedang (<4-10 tahun) 56 orang, ringan (1-4 tahun) mencapai 401 orang (71,1%), dan vonis bebas 68 orang (12,2%). Ilustrasi keabsurdan seolah menggambarkan buah kutukan Dewi Themis dari Mitologi Yunani atau Dewi Yustisia dari Mitologi Romawi, yang terhinakan karena penodaan simbolisasinya. Beban moral dari spirit hukumnya yang terkorup berakhir dengan batu ujian bobroknya peradilan di Indonesia. Simbol keadilan harus dipulihkan.
Ilustrasi keabsurdan seolah menggambarkan buah kutukan Dewi Themis dari Mitologi Yunani atau Dewi Yustisia dari Mitologi Romawi, yang terhinakan karena penodaan simbolisasinya. Beban moral dari spirit hukumnya yang terkorup berakhir dengan batu ujian bobroknya peradilan di Indonesia. Simbol keadilan harus dipulihkan.
Adikodrati dan Kebutaan
Keliru bila berpikir bahwa simbol hanyalah soal penanda (fisik) atau petanda (konsep mental) belaka. Ferdinand de Saussure (2011) dalam karyanya Course in General Linguistics, justru melihat keduanya mampu menghasilkan dualisme dunia yang sepenuhnya konkret sekaligus konseptual di saat yang bersamaan. Struck (2004) menegaskan bahwa simbol modern mengandung bentuk representasi yang memiliki hubungan ontologis dengan referennya (bukan sekadar replikasi mekanis dunia), transformatif dan membuka ranah di luar pengalaman rasional, konkret sekaligus abstrak bahkan transenden, serta padat akan makna yang unik.
Artinya, simbol menyuratkan tanda dan makna yang menghubungkan aspek-aspek abstrak dengan realitas, dan simbolisasinya mampu mendorong semangat, keyakinan, harapan, dan doa, bahkan kekerasan. Misalnya, simbolisme dalam tasbih atau kalung salib, yang bukan hanya tentang identitas keagamaan tetapi juga spirit yang memberikannya sebuah “kekuatan”.
Begitu pula dengan simbol Dewi Themis dan Dewi dengan perlengkapannya seperti pedang (penegakan hukum) dan timbangan (keadilan) menambah kesan bahwa hukum itu sakral yang tidak mengenal status hingga ruang-waktu. Bahkan, penggunaan sosok dewi di era patriarkis kuno sejak era Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan atau Renaisans di abad ke-15, seolah menyiratkan simbol “kesetaraan gender”, aspek keadilan yang didambakan para feminis di seluruh dunia saat ini.
Menurut Coyle dan Ella (2024) dalam tesisnya berjudul “Lady Justice: The Goddess, the Myth, the Legal Metaphor: An Investigation Into the Justice Behind the Visual Metaphor and the Influence of Her Female Form”, dewi keadilan sebenarnya merepresentasikan inti dari konsep keadilan Justinian, yang menyatakan bahwa keadilan adalah “tujuan yang tetap dan konstan yang memberikan hak kepada setiap pria”, sedangkan feminitas dewi keadilan dieksploitasi untuk membantu metafora tersebut mengomunikasikan representasinya tentang keadilan.
Sayang, sosok dewi adikodrati nan perkasa, kehilangan “kekuatannya” ketika memasuki Renaisans di abad ke-15, melalui pemasangan penutup mata sebagai simbol “objektivitas hukum”. Konon, “pencerahan” Renaisans dan aufklärung terhadap rasionalitas dan saintifik, mendorong penghakiman terhadap mistisisme secara membabi buta. Padahal, mata Themis yang tertutup, menurut kutipan dari laman hukumonline.com (2024) dalam artikel “Lambang Keadilan Indonesia, dari Themis hingga Beringin”, memiliki arti tidak ada pandangan yang membawa prasangka dan “buta” memberikan penilaian yang adil dengan hasil yang objektif.
Tapi, di situlah masalahnya. Pikirkan sejenak, dewi dengan kekuatan adikodrati di dunia kuno yang mistis dipaksa menggunakan penutup mata? Kemahakuasaan nampaknya tidak akan terbatas hanya karena benda-benda fana dari manusia. Apalagi, mata Dewi Themis atau Yustisia sendiri diketahui mampu melihat masa depan. Penekanan objektivitas merusak struktur makna simbol mistisisme kuno. Akhirnya, tafsir-tafsir liar, bahkan cenderung meremehkan peran simbol tidak terhindarkan.
Siapa sangka, orang akan melihat dewi keadilan dalam keadaan buta dan mengartikannya sebagai ketidakmampuan peradilan melihat kebenaran yang hakiki. Padahal, adagium “lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” diterjemahkan bahwa peradilan harus terang dan jelas, menghukum secara benar dan tepat, dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan “mata yang terbuka jelas”, layaknya kemahakuasaan Tuhan yang “All Seeing Eye”. Lagi pula, memangnya, pernah ada hakim buta memimpin persidangan di Indonesia?
Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, terjerumus skandal penyuapan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan kasus penyalahgunaan narkoba. Kemudian kisah bertentangan, dilaporkan hukumonline.com (2023) dalam artikel “Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice”, dari kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao seberat 3 kilogram dengan perhitungan harga Rp 2.000 kilogram hingga dijatuhi hukuman 1,15 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan berdasarkan Persidangan Perkara No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt, bukan hanya menyayat hati tapi fakta bahwa hukum tidak boleh buta. Memang, pencurian tidak dapat dibenarkan, baik secara hukum dan perdebatan moral, tapi mengurungnya karena 3 biji buah kakao seberat 3 kilogram? Itu gila dan absurd.
Contoh kasus-kasus di atas adalah tamparan bagi kepongahan manusia yang percaya diri bahwa rasionalitas dan moralitas adalah puncak pencapaian manusia, terlebih ketika berusaha menggeser eksistensi adikodrati dalam kehidupannya. Padahal, hukum yang mati digerakan oleh manusia yang rapuh dan dualistis (baik dan buruk). Seolah keadilan hadir di atas meja judi atau sekadar simulasi survival in the fittest-nya Charles Darwin. Akibatnya, penegakan hukum dan keadilan berubah menjadi pekerjaan berisiko dan rentan. Transformasi simbolis dari aspek mistik menjadi materialistis menurunkan derajat simbol tersebut. Dewi milik Yunani Kuno dan Imperium Romawi, sudah usang tergantikan dengan objektivikasi kering yang konon lebih “nyata” dan “terasa”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, misalnya. Atau, Pohon Beringin, simbolisasi hukum khas Indonesia pengganti Dewi Yustisia, sesuai usulan Saharjo, Mantan Menteri Kehakiman. Kenyataannya sama saja, beban moral penyematan simbol adikodrati kepada humanisasi simbol yang fana telah menjelma menjadi harapan palsu. Padahal, peradilan tidak boleh buta.
Transformasi “keadilan yang tidak pandang bulu” menjadi “keadilan yang tidak punya pandangan”, merupakan komedi bagi mereka yang berkepentingan, dan tragedi bagi kita korban ketidakadilan absurd. Tidak tega, sesosok dewi dipaksa jatuh ke bumi dan mengenakan penutup mata dalam melihat ketidakadilan yang terjadi. Simbol terkorup semacam itu perlu alternatif sebagai jalannya.
Mata dengan Segala-Nya
Renaisans membongkar semua aspek-aspek mistisisme, maka modernitas bisa menjadi jalan untuk membongkar penghinaan kepada simbol hukum ini. Setidaknya, dengan melepas penutup mata yang menyelubungi pandangannya dalam melihat kebenaran sejati. Namun, bila dewa-dewi lama telah kehilangan tempatnya di panggung modernitas, maka alternatif yang lebih prinsipil dan filosofis dari tradisi lama bisa dipertimbangkan. Misalnya, “mata” sebagai simbol hukum. Simbol ini juga pernah digunakan peradaban Mesir Kuno untuk mengilustrasikan Horus maupun Ra, dewa tertinggi mereka, dan diartikan sebagai kesehatan dan perlindungan dari kejahatan. Bahkan, simbol mata masih banyak digunakan dalam konteks modern, dari jimat hingga Dolar Amerika.
Dilek (2021) dalam artikelnya “Eye Symbolism and Dualism in the Ancient Near East: Mesopotamia, Egypt and Israel”, menjelaskan bahwa konsep “mata” di Timur memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar organ yang memungkinkan penglihatan pada makhluk hidup. Berasal dari Mesopotamia, Mesir, dan wilayah tetangga Israel, ia menjelaskan bahwa mata memainkan peran simbolis kunci dan dikaitkan dengan kualitas dualistik dalam keberadaan spiritual masyarakat kuno: baik atau jahat, ilahi atau jahat, protektif atau destruktif.
Penggunaan simbol dalam hukum bukan hanya sekadar stempel dan estetika, tapi juga spirit dan keyakinan. Bahkan, riset Kriviņš, dkk., (2025) menyebut bahwa perilaku legal atau ilegal seseorang sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk memahami simbol dan tanda hukum, serta kualitas stimulus itu sendiri dan informasi terkait dalam konteks sosialisasi dan komunikasi. Sekarang, bayangkan “mata” (keterbukaan, transparansi, kejujuran, pengetahuan tentang segalanya) menjadi alternatif simbol pengganti dewi yang ditutup matanya, bisa jadi penyelidikan kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, akan lebih terbuka, terang, jelas, dan jujur. Dengan demikian, simbolisme mata memberikan kita sebuah pemahaman bahwa Tuhan mengawasi bagaimana manusia menjalankan keadilan di dunia. Termasuk, bagaimana kebenaran “mata” menjadi aspek fundamental untuk mencapai kesempurnaan penegakannya karena Tuhan merupakan pengawas independen langsung. Implementasi dari mata bukan hanya berasal dari kitab-kitab suci, tapi secara esensial termanifestasikan dalam nurani, khususnya kepada penegak hukum di negeri ini.
Pada akhirnya, perdebatan soal simbol itu penting karena menghasilkan spirit tertentu. Namun, praktik hukum konkret jauh lebih penting diperlukan Indonesia saat ini. Misalnya, membangun ekosistem hukum yang berkeadilan, transparan, dan setara, sebagaimana amanat konstitusi pada Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945. Penguatan regulasi dan konsekuensi terhadap seluruh penegak hukum (mereka dianggap lebih tahu hukum), pengawasan institusional dan independen yang akuntabel, dan pertanggungjawaban publik yang dapat memengaruhi kinerja institusi penegakan hukum.
Demikian, pergulatan sengit antara akal-mistisisme simbolik dan falsafah keadilankomedia absurditas hukum Indonesia, berakhir secara anti-klimaks. Esai ini adalah refleksi atas ketegangan rasionalitas dan empati akan moralitas hukum di Indonesia dan dunia. Bagaimana pun, kita tidak bisa mengandalkan selalu sosok mitologi untuk meraih keadilan. Biarkan kekuatan adikodrati bekerja dalam kemisteriusannya. Adapun, kita tetap harus berjuang mencari keadilan sembari mengurus negeri ini. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mestinya memperjuangkan keadilan yang seharusnya diterima, tanpa mengandalkan dan menjatuhkan diri pada kekuatan simbol semata. Apalagi, dunia memang kerap tidak adil, sehingga pembiasaan terhadap ketidakadilan nampak baik, namun bila masih diperjuangkan, mengapa harus berhenti berusaha?

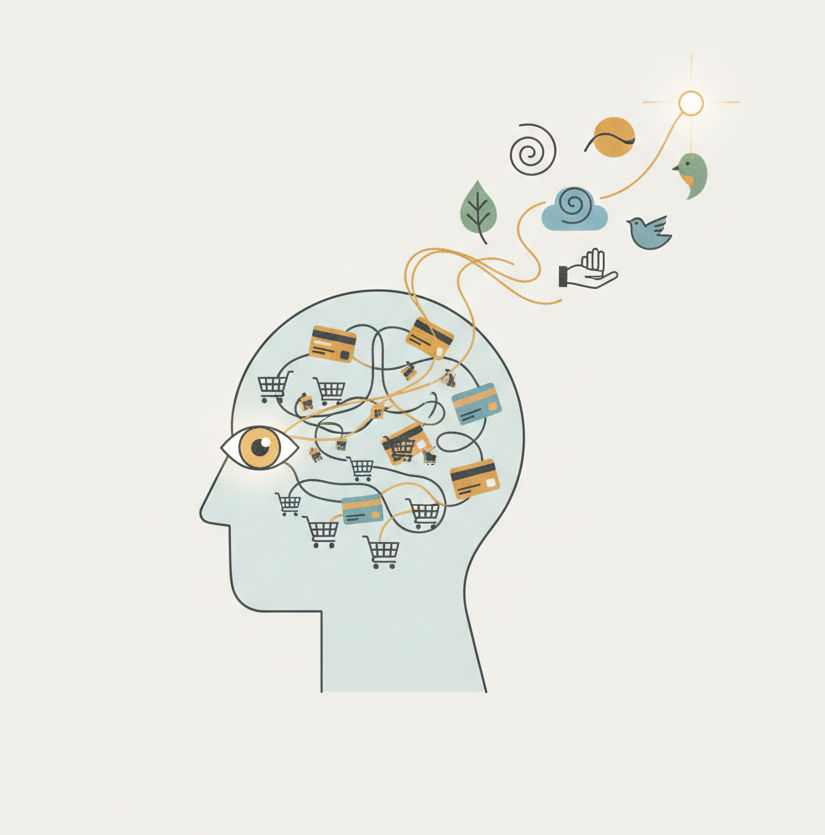


UNICCM School menggunakan Kurikulum Merdeka dalam proses belajar mengajar. Materi disajikan dengan struktur jelas. Kegiatan belajar berjalan terarah.