Hilangnya Esensi Eksistensi Di Era Banjirnya Informasi
- Wildan Budiman Saefulo
- Oct 19, 2025
- 8 min read
Introduksi
Pada era globalisasi yang terdorong oleh proses digitalisasi, kita mungkin sering mendengar tentang pernyataan banyak orang bahwa untuk bisa mensyukuri nikmat ataupun menikmati kehidupan, kita harus mencari makna atau hikmah dari segala yang kita alami. Pernyataan-pernyataan semacam itu muncul karena selama ini kita hanya melakukan dan mengkonsumsi narasi informasi secara repetitif, untuk menghilangkan rasa kejenuhan yang selama ini kita rasakan dalam kehidupan.
Setiap hari kita selalu mengkonsumsi informasi yang bertebaran di realitas virtual maupun realita yang nyata, sehingga terlalu banyak yang perlu kita maknai dan terlalu luas untuk otak kita yang terbatas. Semua menumpuk begitu saja, sehingga pengalaman dan kejadian hanya menjadi tumpukan berkas-berkas yang tidak terbaca. Konsumsi narasi informasi yang terus menerus berulang membuat sebagian orang banal terhadap informasi tersebut.
Ketika seseorang melakukan sesuatu secara repetitif atau berulang-ulang maka lama-kelamaan akan menjadi bosan atau dengan kata lain esensi dari tindakan dan perkataan menjadi hilang. Saya menganalogikannya seperti ada orang yang suka dengan misalnya mie ayam. jika dia makan mie ayam dalam setahun penuh alias 365 hari secara berturut-turut tanpa henti maka orang tersebut pasti akan bosan dan beralih pada hal yang lain. Maka dari itu manusia akan terus menerus berubah-ubah. Bisa jadi individu yang awalnya suka mie ayam menjadi suka nasi padang, yang awalnya religius menjadi orang yang membangkang aturan-aturan agama. Karena didorong oleh sebuah perasaan dimana manusia harus menemukan cara untuk mendapatkan kepuasan yang baru dan menghindari kehilangan makna dari kehidupan itu sendiri. Karena manusia adalah makhluk yang dinamis.
Dalam tulisan ini kita akan menelusuri bagaimana manusia dapat kehilangan makna akibat konsumsi informasi yang berlebihan, dilihat dari berbagai sudut pandang—mulai dari ekonomi, filsafat, hingga ranah religiusitas dan identitas budaya. Melalui perspektif-perspektif tersebut, kita dapat memahami bahwa manusia bukanlah mesin yang bisa diprogram untuk melakukan sesuatu secara berulang tanpa henti; manusia adalah makhluk dinamis yang senantiasa mencari kebebasan atas kehendaknya sendiri. Bahkan di bawah ancaman dan tekanan yang paling keji sekalipun, manusia tetap berusaha mendobrak jeruji yang membatasi kehidupannya, demi menghadirkan warna-warna baru dalam pengalaman hidupnya. Kehidupan, dengan demikian, tidak pernah sederhana hanya berupa hitam dan putih, baik dan jahat, cantik dan buruk. Ia selalu bergerak dalam dinamika yang terus berlangsung, baik disadari maupun tidak.
1. Matinya empati dan hilangnya esensi akibat konsumsi berlebih narasi.
Pada sudut pandang teori ekonomi dari seorang ekonom yang bernama Hermann Heinrich Gossen dalam karyanya yang berjudul The Development of the Laws of Human Intercourse and the Consequent Rules of Human Action (1854) dalam Hukum Gossen I, ia menyatakan:
"The amount of pleasure decreases with every increase in the quantity of the good consumed in a given time."
Artinya: "Kepuasan yang diperoleh dari konsumsi suatu barang akan menurun dengan setiap tambahan unit yang dikonsumsi dalam waktu tertentu."
Ketika narasi dijadikan objek konsumsi yang berulang-ulang, seperti halnya makanan atau hiburan, maka efek emosionalnya akan melemah. Satu narasi memilukan bisa mengguncang hati. Tapi seratus cerita serupa, dalam satu jam, justru membuat kita merasa banal. Konsumsi yang semula dimaksudkan untuk memperluas perspektif dan memperkuat kepedulian malah berubah menjadi aktivitas pasif yang memperlemah daya resap dan penghayatan. Konsep ini dinamakan diminishing marginal utility, di mana bukan hanya kenikmatan yang menurun, melainkan makna dari narasi juga ikut tergerus.
Sama halnya dengan yang ditulis oleh Neil Postman dalam bukunya yang berjudul Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. Technopoly adalah sebuah keadaan budaya, kondisi pikiran dan pendewaan terhadap teknologi, yang berarti budaya mencari otorisasi terhadap teknologi dan menerima tatanannya dari teknologi. Teknologi mendokrak pasokan (supply) informasi. Ketika supply informasi meningkat, mekanisme kendali informasi menegang. Dan ketika pasokan informasi tidak dapat lagi dikendalikan ketenangan psikis dan tujuan sosial pun mulai tergerus. Tanpa pertahanan (kendali informasi), orang tidak memiliki cara menemukan makna dalam pengalaman mereka (Neil Postman, hlm 99-100).
Postman menganalogikannya dengan pertumbuhan sel. Tentu saja pertumbuhan sel adalah proses yang normal. Namun tanpa adanya sistem pertahanan yang yang baik, maka suatu organisme tidak mampu mengelola pertumbuhan sel yang lama-kelamaan akan berubah menjadi sel yang membahayakan yaitu sel kanker (Neil Postman hlm 101). Ketika informasi tumbuh liar tanpa kendali, bukan hanya tubuh sosial yang terganggu, melainkan juga makna narasi itu sendiri.
Bisa jadi Baudrillard ia menunjukkan bahwa yang kita konsumsi hari ini bukan lagi narasi informasi, melainkan tanda, simulacra yang menjauhkan kita dari realitas. Menurut Eno dalam bukunya yang berjudul Bagaimana Media Sosial Menghancurkanmu dia menulis “informasi adalah sesuatu yang diperoleh berdasarkan investigasi, studi, atau instruksi, selain itu membutuhkan kecerdasan, fakta, data dan pemberitaan”. Sedangkan tanda istilah yang digunakan oleh filsuf postmodern Jean Baudrillard dalam bukunya yang berjudul Simulacra and Simulation. Tanda bukanlah realitas sesungguhnya melainkan realitas pseudo, dimana objek itu memiliki makna lain di luar dirinya yang merepresentasikan imajinasi atas objek tertentu (Eno, hlm 10). Dengan kata lain tanda menurut Saussure adalah objek tidak memiliki makna absolut.
Ketika apa yang disebut tanda dikonsumsi secara kolektif maka proses yang kemudian terjadi adalah simulasi. Manusia mulai membentuk realitas pseudonya dan menganggapnya suatu hal yang benar, padahal belum tentu apa yang diintepretasikan adalah kebenaran. Fenomena ini biasa disebut dengan istilah post-truth. Post-truth merupakan kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya tarik emosi dan keyakinan pribadi (Lee Mcintyre: Post-Truth, 2018, hlm 5). Istilah ini hampir sama dengan istilah yang digunakan oleh Baudrillard yaitu simulacrum.
Hal tersebut dapat kita lihat salah satunya melalui fenomena yang ada di media sosial. Seperti dalam lagu The Winner Takes It All yang dinyanyikan oleh ABBA. Makna dari lagu tersebut seharusnya menceritakan orang yang kehilangan harapan, impian dan angan-angannya karena direnggut oleh orang yang menjadi pemenang. Namun saat ini lagu tersebut digunakan untuk mengglorifikasi atau merayakan kemenangan, hanya karena nada lagunya yang seolah merepresentasikan perjuangan. Sehingga lagu tersebut telah kehilangan makna esensinya. Meskipun tidak semua orang melakukan kesalahan dalam memaknai objek, tapi jika hal ini terus menerus dibiarkan maka lama-kelamaan kesalahan ini akan dianggap menjadi satu hal yang biasa. Atau dengan kata lain orang-orang akan menormalisasikan kesalahan tersebut.
Kita yang sekarang hidup di era teknologi yang menawarkan kebebasan dalam bersuara di media sosial telah menyaksikan sendiri bahwa satu objek dapat dimaknai atau diinterpretasikan oleh banyak orang. Ketika semua orang dengan bebas memaknai objek yang mereka konsumsi pada akhirnya hal tersebut akan membuat objek itu perlahan-lahan akan kehilangan makna aslinya. Saya mengutip perkataan dari salah satu karakter dalam seri komik/anime Orb: On the Movements of the Earth yang mengatakan
"Menulis merupakan tanggung jawab besar, jika semua orang bisa menulis maka seluruh dunia akan dipenuhi informasi tidak berguna". ~Badeni (Orb)
2. Hilangnya esensi dari ritus rohani
Di era banjirnya informasi, narasi-narasi tentang keagamaan bagaikan ribuan anak panah diluncurkan dari busurnya tapi tidak satupun yang mengenai targetnya. Seolah target tersebut telah dikunci dan ditutup rapat-rapat oleh Sang Penguasa sehingga Dia tidak membiarkan satu anak panahpun masuk ke dalam hati hambanya. Seperti ketika khutbah Jum'at dikumandangkan, kebanyakan jama'ah yang seharusnya wajib mendengarkan khutbah malah terlelap tidur. Sholawat untuk Nabi tercinta hanya digaungkan secara lantang, tapi tidak "dihidupkan" sehingga kehadirannya tidak kita rasakan. Banyak sekali saat ini ritual-ritual keagamaan hanya dilakukan oleh raga tapi jiwanya mati membusuk terdiam dalam kehampaan. Kebanyakan orang akan beribadah karena ingin mencapai kebahagiaan duniawi semata, meskipun dalam hal ini kita tidak bisa mengadili perilaku orang lain secara langsung akan tetapi jika dibiarkan ketika orang tersebut telah mendapatkan segala hal yang ia inginkan di dunia. Maka saya akan yakin bahwa orang tersebut akan melupakan Tuhannya, karena ibadahnya selama ini hanya berdasarkan nafsu dunia.
Hal yang dikhawatirkan adalah jika matinya narasi-narasi tentang humanisme yang diakibatkan oleh nihilisme kolektif. Jika informasi/narasi tentang pelanggaran terhadap HAM sudah dianggap suatu hal yang banal maka akan ada banyak orang yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Selayaknya era-era peperangan yang menganggap bahwa suatu kerajaan berhak menyerang kerajaan yang lain atas dasar keinginan pemimpinnya untuk menguasai wilayah kerajaan asing, atau seperti suku-suku pedalaman yang masih sering terlibat konflik antar suku yang menganggap membunuh orang selain dari anggota sukunya itu diperbolehkan. Kita tidak dapat menyangkal bahwa manusia selain memiliki sisi yang baik, manusia juga memiliki sisi yang buruk. Namun sisi yang buruk saat ini seringkali dilampiaskan bukan dengan membunuh orang lain melainkan dengan melakukan atau menonton olahraga ekstrem yang menghasilkan hormon adrenalin.
Nihilisme yang dialami secara kolektif dikhawatirkan akan menghilangkan rasa empati. Alih-alih memikirkan nasib orang lain, manusia akan lebih mementingkan keinginan pribadinya. Seperti yang dilakukan oleh rezim zionis Israel yang menyerang Palestina. Untungnya saja masih banyak orang yang memiliki rasa empati terhadap kemanusiaan, namun seringkali diantara mereka yang membela Palestina memiliki standar ganda. Seperti pada konflik antara teroris Houthi dengan pemerintahan Yaman yang mana dalam konflik tersebut Arab Saudi dan UEA ikut terlibat atas penyerangan terhadap teroris Houthi yang mengakibatkan jatuhnya ribuan nyawa korban dari warga sipil. Namun dalam konflik tersebut hampir tidak ada respon apapun atau bahkan tidak dihiraukan oleh netizen pengguna media sosial terhadap penyerangan yang dilakukan oleh Arab Saudi dan UAE di Yaman.
Standar ganda dalam empati tidak hanya terlihat pada konflik global, seperti tragedi di Yaman yang luput dari perhatian publik, tetapi juga merembes ke ranah identitas personal seperti golongan transpuan maupun orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual alias LGBT. Banyak diantara kita yang menghakimi atau menuntut atau bahkan mengutuk kaum LGBT ini karena narasi-narasi dari agama-agama yang kita imani. Tanpa memikirkan alasan rasional dibalik kebencian kita terhadap kaum LGBT ini. Jika spiritualitas bisa kehilangan esensinya, maka budaya pun menghadapi nasib serupa.
3. Globalisasi dan Hilangnya Identitas Diri
Globalisasi telah menghapus pembatas baik jarak maupun batas negara. Setiap dari negara memiliki ciri khas budaya, nilai dan normanya masing-masing, namun sekarang semuanya telah berubah. Dulu ketika kita masih memberlakukan standar nilai dan norma masyarakat sekitar, tapi di dalam sosial media nilai-nilai dan norma tersebut tergerus dengan standar norma masyarakat multinasional. Seperti halnya di Indonesia yang melarang unggahan berbau pornografi, tapi di sosial media yang aturannya diatur oleh orang memiliki standar norma yang berbeda maka norma kita menghilang dan tak lagi diterapkan di dalam realita maya tersebut. Sama halnya dengan budaya yang seharusnya kita jaga kelestariannya, tapi globalisasi akan terus-menerus mengikis budaya nenek moyang yang seharusnya menjadi identitas kita sebagai sebuah bangsa. Realita terdistorsi dengan "kehidupan" dunia maya.
Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini. Tak mengenal di negara manapun manusia itu hidup, juga mengalami hal yang serupa. Seperti dalam buku Kita & Mereka karya Agustinus Wibowo menceritakan masyarakat suku pedalaman yang terpapar oleh internet tak lagi menerapkan budaya standar kecantikan yang telah nenek moyang mereka terapkan. Cara hidup, nilai, norma dan budaya manusia yang dulu heterogen berubah menjadi budaya yang homogen. Budaya tak lagi dikenal sebagai identitas melainkan hanya sebagai daya tarik pariwisata. Tujuan pelestariannya tak lagi didasarkan pada ajaran filosofis nenek moyang melainkan hanya dijadikan objek material yang dapat dikomersilkan. Sehingga budaya-budaya tersebut kehilangan nilai esensinya.
Jika sudah menyangkut dengan kebudayaan maka akan sangat berkaitan erat dengan gaya hidup masyarakat. Masyarakat di era ini tak lagi memikirkan makna dalam hidup mereka. Mereka hanya memikirkan kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam kehidupan atau biasa disebut dengan istilah hedonisme. Mencari pekerjaan tidak lagi berdasarkan esensinya melainkan juga dijadikan ajang validasi ataupun ketenaran. Semua didasarkan pada pemikiran materialisme karena segala ranah kehidupan kita dibalut oleh jerat kapitalisme. Ketika seseorang tidak mendapat apa yang dia inginkan maka dia akan merasa kehilangan makna hidupnya. Karena semua itu dilakukan bukan berdasarkan pada esensinya tapi untuk mendapatkan validasi dari orang-orang disekitar dan di realita maya (sosial medianya). Setiap kebahagiaan yang ia dapatkan tak akan lupa untuk diunggah di sosial media. Seolah-olah jika dia tidak mengunggahnya maka menganggap eksistensi dirinya tidak ada. Meskipun sebagian beralasan bahwa hal tersebut adalah bentuk kebanggaannya terhadap apa yang ia capai, namun dalam lubuk hatinya ia hanya ingin memuaskan nafsu epithumia atau hasrat mendapatkan kehormatan. Keangkuhan berawal dari rasa kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan. Sombong berawal dari sifat bangga yang berlebihan sehingga melahirkan sifat keegoisan.
Kesimpulan
Hilangnya makna dari eksistensi di era banjir informasi memperlihatkan paradoks kehidupan manusia modern. Di satu sisi, manusia diberi akses tanpa batas terhadap narasi, simbol, dan ritual; namun di sisi lain, kelimpahan tersebut justru melemahkan daya resap, mengikis empati, serta mereduksi esensi menjadi sekadar repetisi. Teori Gossen tentang penurunan kepuasan, kritik Neil Postman atas dominasi teknologi, hingga gagasan Baudrillard tentang simulacra menunjukkan bahwa makna kini lebih sering tergantikan oleh tanda semu dan validasi sosial.
Fenomena ini tidak hanya memengaruhi aspek kultural dan sosial, tetapi juga religiusitas, di mana ritus keagamaan kerap kehilangan roh spiritualnya. Globalisasi dan kapitalisme semakin menambah lapisan masalah dengan menyeragamkan budaya, menjadikan identitas hanya sebagai komoditas pariwisata atau ajang pencitraan. Akibatnya, manusia kerap terjebak dalam nihilisme kolektif yang mengaburkan orientasi hidup.
Namun demikian, sebagai makhluk dinamis, manusia tetap memiliki peluang untuk merebut kembali otentisitas eksistensinya. Kesadaran kritis terhadap bahaya konsumsi berlebih, banalitas narasi, dan distorsi makna menjadi langkah awal untuk menjaga ruang refleksi personal. Dengan demikian, tantangan utama di era ini bukan sekadar bagaimana manusia mencari makna, melainkan bagaimana ia mampu mempertahankan esensi di tengah arus informasi yang tiada henti. Akhir kata saya ingin menegaskan bahwa “Makna itu rapuh. Ia bisa hilang dalam repetisi. Ia bisa tenggelam dalam banjir informasi”

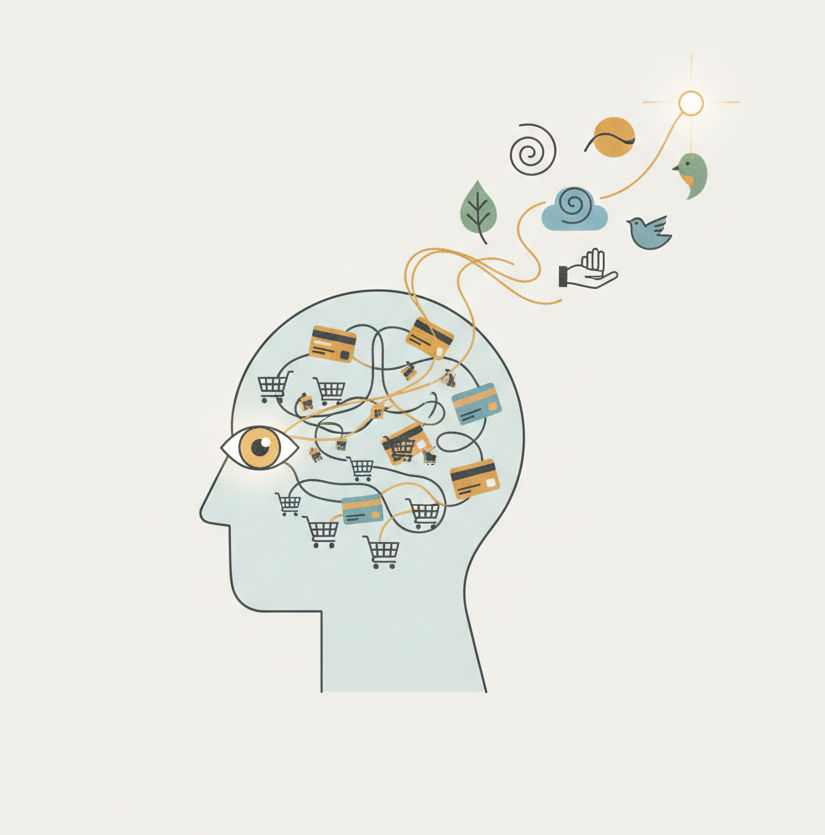


Comments